Sudah lebih dari tiga tahun aku tak pulang kekampung halamanku. Memang itulah resiko yang harus aku tempuh jika sudah menjadi anggota TNI. Siap dibuang kemana saja dan kapan saja. Sudut-sudut kampungku rupanya telah berubah drastis. Aku hampir saja tak mengenalinya. Hari pertama di kampung memang sudah kurencanakan untuk putar-putar dan melihat pemandangan alamnya. Semua rumah sudah tampak megah sekarang. Tak seperti dulu. Semua rumah reot, cuma ada satu rumah yang tampak mewah. rumah Pak Kades. Siapa lagi kalau bukan dia. Orang paling tersohor di kampung.
Lama juga aku tak melihat rumahnya. Segera kukayuh sepeda tuaku kearah rumah Pak Kades.
“Masih seperti dulu”batinku. Tak ada yang mau merenovasi. Rumah itu masih tampak kotor dan lusuh. Tak ada warga yang berani membersihkan dan memindahkan puing-puing rumah itu. Pikiranku menerawang. Anganku membawaku menyusuri ruang masa lalu.
Saat itu aku baru berumur tujuh tahun. Seperti layaknya anak-anak seumuranku, aku dan teman-temanku biasa menghabiskan waktu kami untuk bermain. Kami mempunyai tempat favorit untuk bermain. Di bawah pohon mangga dekat lapangan sepak bolalah kami biasanya melakukan berbagai macam permainan. Mualai dari lompat tali, tangkap kejar, main gundu, layang-layang, bahkan bermain sepeda ontel tua milik ayahku.
“Min! lekas pulang!” teriak Pak Mi’un . Dia adalah kepala desa kami, termasuk orang terkaya dan paling terpandang di desa kami.
“Tapi Pak, Amin kan baru sebentar mainnya” rengek Amin.
“Kalau main terus besok gede kamu mau jadi apa. Sana lekas pulang dan belajar”
Kasihan Amin, padahal baru kali ini ia bisa ikut bermain tapi sudah disuruh pulang orang tuanya. Memang begitulah sifat Pak Kades. Ia memang tidak pernah suka dengan anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk bermain. Itu cuma memubadzirkan waktu, katanya.
Sebagai akibatnya, anaknyalah yang jadi korban. Amin memang anak satu-satunya pak Kades. Jadi Aminlah yang jadi korban hasrat orangtuanya yang berlebihan. Pak Kades termasuk Bu Kades ingin agar anaknya suatu saat bisa menjadi dokter. Tentu saja dengan harapan kelak masa depan anak sekaligus mereka bisa terjamin.
Aku adalah teman karib Amin. Ia kerap kali mengeluh tentang orang tuanya, lalu dilanjutkan dengan menangis di hadapanku. Katanya orang tuanya terlalu menekannya. Ia sama sekali tidak betah dirumah. Tapi untungnya Amin adalah anak yang baik dan penurut. Ia sama sekali tidak pernah membantah perintah orang tuanya.
Terkadang aku juga sempat menitikkan air mata jika memikirkan nasib Amin. Ia adalah anak yang polos. Dalam hal pelajaran ia biasa-biasa saja. Dan kalau boleh jujur sebenarnya ia termasuk anak yang kurang pintar. Tiap kali ia mendapatkan nilai jelek pada kertas ulangannya. Pasti ia akan menangis karena takut kalau akan diomeli orang tuanya. Sempat beberapa kali aku menukar kertas ulangannya dengan kertasku. Tulisanku hampir mirip dengan tulisan Amin. Dan nilaikupun biasanya lebih bagus darinya. Dan nyatanya berhasil. Orang tua Amin akhirnya bisa juga tertipu. Ia tak jadi dimarahi dan biasa setelah itu ia mentraktirku dua buah bakwan.
Tapi itu kalau kertas ulangan. Sebaik apapun kami tutupi toh nyatanya saat penerimaan raport hal itu akan terungkap.
Setelah lulus SD kami berpisah. Ia masuk di SMP 3, tempat anak-anak orang kaya biasa bersekolah. Sedangkan aku masuk SMP 10, sebuah sekolah yang biasa dimasuki anak-anak dari ekonomi menengah kebawah. Meski begitu ia tak lupa dengan kebiasaannya mentraktirku. Sebulan sekali biasanya kami jalan-jalan kekota, sekedar menghilangkan penat masing-masing dan saling bersendau gurau.
Setelah lulus SMP ia diperintah ayahnya untuk melanjutkan SMA di Jogja. Katanya supaya bisa terbiasa dengan suasana Jogja. Maklumlah, rencananya sehabis lulus SMA Amin akan langsung di masukkan kesalah satu Univeritas terkemuka jurusan kedokteran yang ada di Jogja.
Aku sendiri menghabiskan SMA ku di kotaku sendiri dan meneruskan ke salah satu perguruan tinggi di Jogja. Tapi tentu saja perguruan tinggi yang termurah. Bukannya aku mau sok kuliah di Jogja, tapi hal itu tiada lain karena di kotaku memang belum ada perguruan tinggi.
***
Amin kini sudah masuk di Universitas yang dikehendaki ayahnya. Tapi dikarenakan kemampuan intelejen Amin yang pas-pasan maka tak ayal lagi ayahnya harus merogoh kocek lebih dalam. Pak Mi’un sudah tidak jadi kades lagi saat ini. Ia sudah tak berminat lagi jadi kades. Karena menurutnya masa depan cerah sudah ada di depan mata. Jadi uang yang sedianya ia gunakan untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan kades, ia alihkan untuk membiayai seluruh keperluan anaknya. Bahkan beberapa hektar tanahnya juga ia putuskan untuk di jual demi pendidikan anaknnya.
Kini pak M’iun Cuma seorang petani. Dari hasil tani itulah ia mencukupi segala kebutuhannya. Ia bukan lagi orang yang terpandang di kampung. Ia cuma seorang petani biasa yang punya hasrat setinggi langit. Bukannya punya cita-cita itu jelek. Tapi kalau sudah keterlaluan kan tidak baik.
Saat menginjak kuliah aku memang sangat jarang sekali bertemu dengan Amin. Kami sibuk dengan urusan masing-masing. Tetapi menurut berita yang kudengar ia masih saja seperti dulu. Nilainya pas-pasan dan bahkan cenderung buruk.
Pernah satu kali kami janjian bertemu di salah satu warung di malioboro. Ia bukan lagi Amin yang seperti dulu. Walaupun merasa tersiksa, tapi dahulu ia msih sempat tertawa riang jika bersamaku. Kini ia jadi pendiam. Aku sama sekali kehabiasan bahan omongan untuk aku biacarakan kepadanya. Karena ia hanya sedikit menaggapi omonganku.Dan itupun dengan nada yang sangat dingin.
***
Waktu berlalu begitu cepat. Kini tiba hari diamana aku akan mengakhiri masa belajarku di Perguruan Tinggi. Aku lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Orang tuaku cukup bangga dengan hal itu. Kami pulang bersama kekampung dengan seluruh barang bawaanku selama aku tinggal di kos.
Orang pertama yang menyambutku dirumah bukanlah tetangga dekatku. Melainkan pak Mi’un. Bukan hendak memberikan selamat, tapi ia justru ingin tahu kabar anaknya yang ada di Jogya. Karena sudah lama Amin tidak kasih kabar.
“Gimana kabar Amin?”
“Kapan Wisudanya?”
“Nilainya bagus tidak?”
Aku bingung harus menjawab apa. Tak ayal aku terpaksa harus sedikit berbohong. Dua bulan kemudian aku melamar menjadi anggota TNI. Untuk latihan pertama aku harus pergi selama lima bulan.
Ketika aku pulang, ternyata ada hal yang sangat memilukan yang terjadi didesaku. Selepas kepergianku Amin pulang kekampung. Ia mengaku tak mampu lagi melanjutkan studynya. Ia merasa sangat tertekan karena semua teman satu angkatannya sudah diwisuda. Pak Mi’un tentu saja yang paling terpukul. Tapi bukan itu yang membuat warga kampung geger.
Tak lama berselang, Amin terjangkit penyakit kejiwaan dan menjadi gila. Dan pada suatu malam, tanpa sepengetahuan orang tuanya ia membakar semua yang ia miliki. Rumah, Orang tua dan nyawanya sendiri.
Hari sudah menjelang senja. Aku harus segera pulang karena orang tuaku pasti akan kebingungan mencariku. Segera kukayuh sepeda tuaku untuk pulang ke rumah. Dalam perjalan itu kulewati pohon mangga tempat kenangan kami yang kini sudah kering di makan masa.
...
Rabu, 09 Januari 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

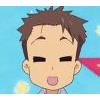
1 komentar:
mas cerpennya bagus...
tapui...sungguh terlalu....
preeeeeeeeet.....
Posting Komentar